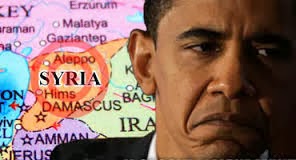Di bagian pertama tulisan
yang pernah diangkat mengenai diaspora ini, penulis pernah menutupnya dengan kalimat bahwa
seandainya diaspora ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka niscaya tidak akan
atau akan dimanage dengan baik seperti halnya peristiwa pembukaan kantor cabang
papua merdeka di Inggris beberapa waktu lalu. Melalui tulisan ini, penulis
ingin mencoba mengangkat kembali tema diaspora, namun dengan judul yang
berbeda, yaitu bagaimana diaspora dijadikan sebagai alat perjuangan politik.
Diaspora seperti yang sudah
diilustrasikan di bagian pertama, dan apabila dikaitkan dalam konteks diaspora
Indonesia, hal tersebut merujuk kepada semua orang yang berada di luar negeri
yang berdarah, berjiwa, dan berbudaya Indonesia, baik yang masih WNI maupun
yang sudah menjadi WNA. Dengan kata lain, seandainya seseorang tersebut masih
memiliki suatu ikatan batin, baik secara legal (tercatat sebagai warga Negara)
maupun kultural, hal tersebut bisa dikatakan sebagai diaspora. Sebenarnya,
fungsi diaspora ini bisa juga dijadikan fungsi politik, seperti yang terjadi
pada saat segelintir rakyat Aceh ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) di era 2000an silam.
Dalam bukunya yang berjudul “Politik
Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran Tentang Konflik Separatis di Indonesia”
yang merupakan hasil dari penelitiannya, Antje Missbach, seorang peneliti dari
Melbourne University, mengungkapkan bahwa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dengan Republik Indonesia kemungkinan tidak akan berlangsung lama
seandainya tidak didukung oleh komunitas diaspora Aceh yang berada di luar
negeri. Adapun dikatakan beliau peran komunitas diaspora antara lain:
1. Pertama,
komunitas diaspora dapat mencoba memberikan pengaruh langsung bagi peristiwa di
tempat asalnya dengan cara memberikan bantuan politik dan ekonomi bagi
pergerakan kelompok sejawat di tempat asal (homeland
country). Hal yang sama dilakukan dalam revolusi Cina di tahun 1911 dimana
revolusi tersebut tidak bisa terlepas dari adanya dukungan finansial dari kaum
perantauan. Selain itu seperti peristiwa yang terjadi di Jerman dalam hal ini
komunitas Kroasia yang memasok senjata dalam mendukung etnis Kroasia untuk
memisahkan diri dari Yugoslavia. Hal yang sama terjadi di Komunitas Diaspora Irlandia
di Amerika Serikat yang mendukung secara finansial perlawanan IRA untuk
mendirikan Republik Irlandia.
2. Yang
Kedua adalah, komunitas Diaspora dikatakan oleh Antje Missbach kemungkinan
dapat melakukan mobilisasi segenap kekuatan mereka untuk mempengaruhi Negara penampung
(host country) agar mengeluarkan
politik luar negeri yang menekan Negara asal mereka (homeland country) untuk berkompromi dengan mereka mengenai hal-hal
tertentu. Contoh dari yang kedua ini adalah bagaimana komunitas Diaspora Yunani
melobi kongres Amerika Serikat untuk melakukan embargo bantuan militer bagi
pemerintah Turki dalam peristiwa upaya pemisahan Negara Siprus. Hal serupa
dapat dilihat dalam peran komunitas diaspora Afrika Selatan dalam mempengaruhi
senat Amerika Serikat untuk menentang kebijakan Apartheid pemerintah Afrika
Selatan. Hal inilah yang kemudian ditiru oleh komunitas diaspora Aceh, dimana
mereka mempengaruhi pemerintah Swedia untuk menekan pemerintah RI agar mau menghentikan
kekerasan dan membuka pintu perundingan.
3. Yang
terakhir adalah, dalam kasus tertentu, mungkin saja komunitas diaspora dapat
meminta perlindungan dari Negara asal (homeland
country) agar membebaskan mereka dari perilaku diskriminatif, perlakuan
tidak adil, dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Sebagai contoh adalah berbagai
kelompok diaspora yang terbentuk dari migrasi ekonomi sebagaimana dilakukan
kaum diaspora Turki di Jerman dan kelompok diaspora Aljazair di Perancis dalam
melobi pemerintah Negara asalnya untuk menekan pemerintah Negara penampung agar
lebih memperhatikan hak-hak mereka.
Terlepas dari itu semua, benar
dikatakan oleh Dubes Dino Patti Djalal dan rekan-rekan Diaspora Indonesia
dimanapun berada, bahwa komunitas diaspora ini merupakan asset yang sangat
penting yang patut untuk dijaga. Selama ini, orang Indonesia telah banyak yang
melakukan perantauan baik menetap sebagai warga Negara di suatu Negara, ataupun
hanya tinggal di sana untuk menuntut ilmu dan bekerja di sana. Namun demikian,
dikatakan oleh Dubes Dino Patti Djalal bahwa hal tersebut sangat disayangkan
dimana ternyata mereka tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Bisa jadi
seorang “Indonesia” tersebut tinggal di Houston tetapi tidak kenal dengan yang
berada di New York. Hal inilah yang ingin diperbaiki dengan adanya kongres
Diaspora Indonesia. Banyal ide-ide cemerlang dari mereka, tetapi selama ini
tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Selain itu,
keberadaan orang Indonesia di luar negeri selama ini telah tercemar dengan
hal-hal negatif dimana kebanyakan orang menganggap bahwa orang Indonesia yang
bekerja di luar negeri selalu diasosiasikan sebagai pekerja kasar (buruh).
Padahal tidak demikian adanya. Hal inilah yang kemudian dianggap perlu dilakukan
perubahan mindset.
Dalam kaitannya dengan diaspora
sebagai alat perjuangan politik, pemerintah Indonesia melalui komunitas
diaspora sebenarnya dapat memperoleh keuntungan yang besar. Karena dengan
adanya komunitas ini, pemerintah Indonesia dapat melakukan counter-politic terhadap komunitas diaspora separatis yang berada
diluar negeri. Sebagai contoh, adanya pembukaan kantor cabang papua merdeka di
Inggris. Hal tersebut dapat di counter dengan me-lobby ataupun menekan
pemerintah tempat kantor tersebut dibuka agar membatalkan pembukaan kantor
tersebut. Dengan demikian peristiwa tersebut tidak perlu sampai dimuat di media
massa. Selain itu, dengan adanya komunitas diaspora di manapun berada,
sebenarnya dapat menjadi suatu jaringan intelejen terhadap upaya pemisahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan dari komunitas yang ingin memisahkan
diri yang berada di luar.
Dengan banyaknya manfaat
tersebut, sekarang tinggal bagaimana caranya pemerintah Indonesia melakukan
upaya positif yang menggalang kekuatan diaspora yang berada di seluruh dunia
untuk bersama-sama membangun Indonesia, di fasilitasi, dan dilakukan upaya
konkrit dimana ide dan segala bentuk sumbangan mereka dapat dilaksanakan di
Indonesia. Jangan sampai respon positif yang dilakukan teman-teman diaspora
tersebut justru kemudian berbuah kekecewaan besar karena respon lambat dari
pemerintah yang tidak mau berubah dan mendapatkan masukan dari mereka. Dan
jangan sampai deklarasi diaspora Indonesia yang disampaikan di Los Angeles 2012
lalu dalam berbagai bahasa dan dicap sebagai Sumpah Pemuda Ke-II bangsa
Indonesia berubah menjadi suatu sumpah yang bersama-sama tidak peduli kepada
tanah air, atau leluhurnya: Indonesia.
Sumber:
1. Paradigma Diaspora Dalam Diplomasi Indonesia, Dr. Dino Patti Djalal, Jurnal Diplomasi: Peran Diaspora Indonesia, 2012
2. Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Konflik Separatis di Aceh, Antje Missbach, Penerbit Ombak, 2012